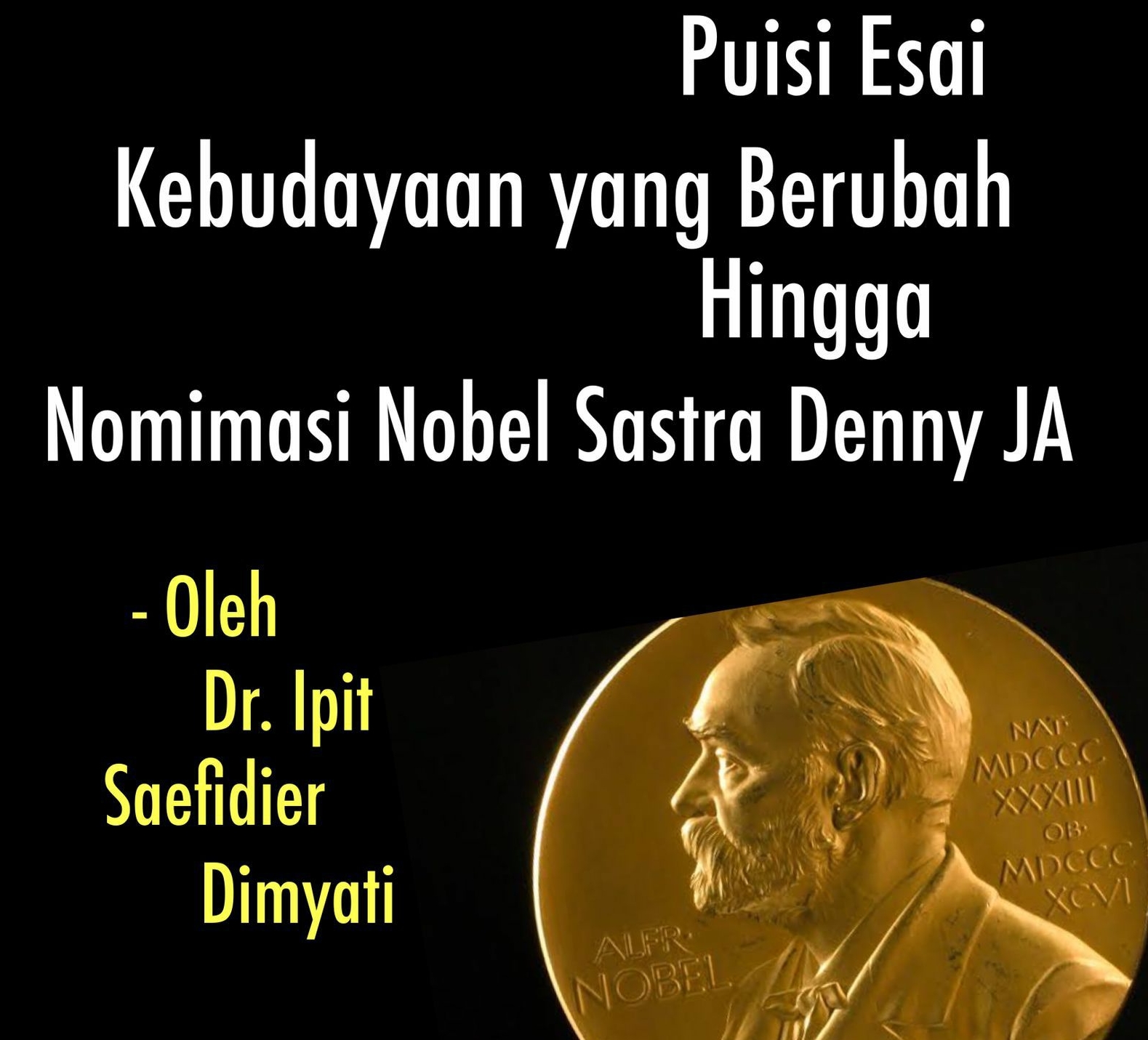Oleh : Ipit Saefidier Dimyati
Dalam khazanah puisi Indonesia, hanya ada tiga penyair yang berhasil melakukan lompatan kreativitas: Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri dan Denny JA.
Kehadiran Denny JA di dunia sastra Indonesia terbilang unik. Ia dipuja dan sekaligus dihujat.
Puisi Esai, bentuk yang relatif baru dalam penulisan puisi, terlihat sangat menghenyakkan dunia sastra. Setelah polemik perdebatan sastra kontekstual yang dipicu oleh tulisan Arief Budiman di Majalah Sastra Horison, yakni sekitar tahun 1980-an, sastra Indonesia dalam persoalan wacana cukup terdiam lama.
Puisi esai dipuja karena telah membawa angin segar bagi perkembangan dunia sastra Indonesia, bahkan mancanegara, dengan menawarkan bentuk yang baru.
Ia dihujat karena Denny JA, penggagas puisi esai, dianggap sebagai new comer dalam dunia sastra, tiba-tiba masuk menjadi salah satu dari 33 sastrawan Indonesia yang paling berpengaruh.
Terlepas dari “pro” dan “kontra” tersebut, dalam tulisan yang pendek ini saya mencoba untuk memahami orisinalitas yang termaktub dalam puisi esai.
Puisi Esai yang digagas Denny JA adalah penyimpangan. Penyimpangan dari penulisan puisi yang biasa.
Jika umumnya, seni itu dianggap sebagai fiksi belaka, maka dalam puisi esai, fakta disertakan pula. Mungkin kita bisa menyanggahnya dengan mengatakan, dalam puisi-puisi yang lain pun kerap penyairnya menyertakan fakta-fakta. Misalnya karya Chairil Anwar, “Kerawang-Bekasi”, bukankah nama kedua kota yang menjadi judul puisi itu merupakan fakta atau sesuatu yang nyata?
Jika sekadar menyebutkan nama tempat, benda-benda, atau peristiwa-peristiwa yang nyata, tentu saja itu banyak penyair telah menncantumkannya di dalam puisi-puisi mereka.
Akan tetapi, dalam puisi esai, paling tidak di dalam karya-karya Denny JA, fakta dihadirkan bukan sekadar menjadi latar belakang atau untuk menyimbolkan sesuatu, tetapi fakta-fakta itu menjadi faktor intrinsik yang dominan.
Kemudian, dan ini yang paling penting, fakta-fakta itu dikuatkan dengan menambahkannya catan-catatan kaki. Umumnya bentuk catatan kaki digunakan dalam karya-karya ilmiah, tetapi dalam puisi esai catatan kaki menjadi bagian puisi yang integral.
Penyimpangan puisi esai tidak terletak pada subject matter dan media yang digunakan, tetapi pada bentuk ungkapan yang dipilihnya.
Puisi, seperti halnya karya-karya seni yang lain, yang diciptakan oleh seorang penyair, memiliki tiga susunan:
- Subject matter atau isi yang ingin diungkapkan;
- Medium untuk mengungkapkan; dan
- Bentuk (cara) untuk mengungkapkan.
Seniman (modern) selalu terobsesi untuk mencari orisinalitas, baik dalam isi, medium, maupun cara mengungkapkannya.
Akan tetapi, dari ketiga susunan tersebut, bentuk merupakan susunan yang paling siginifikan dalam menandai keotentikan seorang seniman dalam berkarya.
Subject matter, atau kalau suka sebut saja “tema”, meskipun tidak dalam setiap karya seni memiliki tema, yang ingin disampaikan oleh seorang seniman terhadap penikmatnya, bisa saja sama dengan seniman yang lainnya.
Misalnya, bila kita menafsirkan bahwa, isi atau tema yang ingin disampaikan oleh Sophocles dalam Oedipus Rex adalah “siapa yang melawan alam akan dihajar oleh alam”, maka tema tersebut bisa saja ditiru oleh seniman yang lainnya dalam karya yang berbeda.
Dan ini dapat dilakukan tanpa seniman bersangkutan dilabeli sebagai plagiat. Begitu pula dalam pilihan medium. Seniman itu bisa memilih medium yang menjadi alat ungkapnya.
Pilihan medium hanya menentukan bahwa seni yang diciptakannya itu masuk ke dalam kategori seni tertentu. Jika ia memilih medium kata, maka karyanya termasuk sastra, jika pilihannya pada bunyi, maka seni yang dibuatnya masuk ke dalam musik, jika mediumnya ruang, garis dan warna, maka karya yang dibuatnya termasuk karya seni rupa, dan sebagainya.
Umumnya orisinalitas karya seni dilihat dari bentuk yang dibuat seniman untuk mengungkapkan subject matter mereka. Artinya, suatu karya dikatakan orisinil dan mempunyai keotentikan jika bentuk yang disajikannya itu khas, unik, dan belum pernah dibuat oleh orang lain.
Seseorang menyebut bahwa, karya seorang seniman itu sebagai karya plagiat, atau paling tidak mengekor terhadap seniman lain, karena bentuk yang disajikannya relatif sama atau mirip dengan yang pernah dibuat oleh seniman sebelumnya.
Mengenai kebaruan suatu karya seni tentu saja bisa diperdebatan, karena, seperti yang dikatakan sebuah pomeo, “tak ada yang baru di bawah matahari”.
Keotentikan atau orisinalitas suatu karya seni tampaknya memang kurang tepat jika dikatakan sebagai “baru”, tapi merupakan hasil dari penyusunan hal-hal yang sudah ada dengan cara yang berbeda.
Bila cara-cara penyusunan yang berbeda yang dibuat seniman itu belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, maka dikatakan bahwa karya itu orisinal.
Karya yang orisinal dari seorang seniman, jika kemudian polanya tersebut diikuti oleh seniman-seniman lainnya secara masif, maka jadilah aliran.
Setiap aliran dalam karya seni seperti realisme, surealisme, dadaisme, dan romantisme, awalnya dicetuskan oleh seorang atau beberapa seniman, kemudian polanya diikuti oleh seniman-seniman lainnya, dan akhirnya pengamat seni atau kritikus melabelinya dengan “isme” tertentu.
Puisi esai merupakan bentuk penulisan puisi yang sebelumnya tidak ada. Persoalan-persoalan sosial yang jadi pokok soal yang diangkat dalam pusi esai bisa dikatakan bukanlah sesuatu yang terlalu istimewa, karena dalam puisi-puisi penyair yang lain pun pokok soal serupa itu kerap pula dilakukan.
Yang menjadi istimewa adalah persoalan-persoalan sosial itu dalam puisi esai disajikan sebagai fakta-fakta yang dominan, dan kemudian fakta-fakta itu diperkuat dengan catatan-catatan kaki seperti tulisan-tulisan dalam karya ilmiah atau esai.
Meskipun begitu, bukan berarti puisi esai menjadi karya ilmiah. Puisi esai adalah karya seni yang melibatkan respon subyektif senimannya terhadap fakta-fakta objektif.
Fakta objektif dalam puisi esai menjadi latar yang menunjukkan bahwa penyair sebagai subyek memiliki keterlibatan dengan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekelilingnya.
Itulah keorisinalitasan puisi esai dan keberbedaannya dari puisi-puisi yang sudah ada. Inilah kiranya yang patut kita apresiasi.
Dalam khasanah perpuisian di Indonesia, menurut pandangan saya, hanya ada tiga penyair yang pernah melakukan semacam “lompatan” kreativitas dalam penulisan puisi.
Pertama, Chairil Anwar, yang menulis puisi secara bebas dan keluar dari pakem-pakem pola pantun yang dominan di saat itu.
Kedua, Sutardji Calzum Bachri, yang mencoba mengatasi pengaruh Chairil Anwar dengan kembali ke semangat mantra serta menghindari kata-kata hanya sebagai saluran ide.
Ketiga, Denny JA, dengan membuat dan menawarkan gagasan puisi esai, yang membaurkan antara fiksi dan fakta yang termuat dalam badan puisi ataupun catatan kaki.
Bila dilihat dari perspektif kebudayaan yang berubah, puisi esai awal kemunculannya berada dalam ranah liminal, artinya bahwa bentuk puisi yang ditawarkan oleh Denny JA itu belum menjadi bagian kebudayaan yang dominan.
Namun, karena sudah muncul ke permukaan, ia bukan lagi sebagai potensi yang terbenam dalam “cadangan” kebudayaan.
Puisi esai seolah-olah berada dalam kondisi in-between, yakni berada di ambang antara kebudayaan dominan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu kebudayaan.
Reaksi-reaksi yang muncul, baik yang “pro“ maupun yang “kontra“, bisa dimaklumi, sebab di samping ia menjadi peluang untuk berkreativitas bagi orang-orang yang mungkin sudah merasa jenuh dengan gaya dan pola yang lama, bagi sebagaian orang lagi kehadirannya itu dianggap dapat mengganggu kedamaian dan kenyaman kondisi yang sudah tercipta.
Mereka tidak suka terganggu mungkin karena kondisi yang lama telah memberi posisi yang nyaman dan tentram, dan oleh sebab itu ketika ada yang mengusiknya, mereka memberikan respon yang berlebihan.
Kondisi berada di ranah liminak bisa saja terjadi dalam waktu yang lama atau bisa pula sebaliknya, yakni diterima dengan cepat oleh masyarakat.
Sebelum menjadi bagian integral dari kebudayaan dominan, biasanya sesuatu yang relatif baru, seperti halnya puisi esai, akan direpresi agar tidak muncul ke permukaan.
Represi itu bisa dalam bentuk yang beragam, seperti misalnya tidak disediakan ruang untuk tampil, ataupun bila ditampilkan dia dibingkai dalam suatu peluang yang dilabeli dengan penamaan-penamaan yang berkonotasi negatif, dan sebagainya.
Tentu saja tujuannya agar masyarakat tidak tertarik atau tidak turut serta ke dalam arus yang mengalir dari karya yang baru tersebut.
Jika masyarakat tertarik dan ikut serta dalam gerakan perubahan itu, seperti sudah disebutkan, posisi-posisi yang telah diduduki oleh orang-orang yang berkepentingan untuk tetap dalam situasi stagnan, menjadi lemah, dan tak lagi signifikan.
Sejak diterbitnya buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, gagasan puisi esai mendapatkan tantangan penolakan yang bertubi-tubi. Namun di samping itu pun ada pula gerakan-gerakan yang mendukung kemunculan bentuk puisi esai tersebut.
Jejak-jejak digital tentang perdebatan mengenai puisi esai itu bertebaran di berbagai web, situs, atau media-media konvensional seperti majalah dan koran.
Kiranya perlu ada orang yang berinisiatif untuk membukukan perdebatan tersebut sehingga menjadi dokumen yang bermanfaat di masa depan.
Satu hal yang bisa kita baca dari perdebatan itu, bahwa kehadiran puisi esai telah memberikan semangat baru bagi perkembangan sastra Indonesia dan juga dunia.
Penolakan-penolakan terhadap kehadirannya mulai mereda, dan justru di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun mancanegara seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, tumbuh komunitas-komunitas yang berkonsentrasi pada penciptaan puisi esai.
Puisi Esai juga dengan cepat sudah masuk menjadi entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bila pada awalnya puisi esai dianggap oleh sebagian orang sebagai penyimpangan, kini tampaknya mereka mulai ramai-ramai menerimanya sebagai karya puisi yang juga patut diapresiasi.
Puisi esai kini menjadi sebuah genre yang mengatasi penciptaan-penciptaan puisi sebelumnya.
Sebagai warga Negara Indonesia saya cukup bangga dengan kehadiran puisi ini, sebab gemanya tidak hanya terdengar di dalam negeri, tapi juga menembus ke berbagai Negara.
Kini bahkan tersiar kabar bahwa Panitia Nobel, The Swedish Academy (The Nobel Committee) secara resmi mengundang perwakilan komunitas puisi esai Indonesia untuk menominasikan Denny JA. Sebagai penerima Nobel.
Selama sejarah hadiah Nobel untuk sastra diberikan, belum pernah seorang pun sastrawan Asia Tenggara menerimanya. Orang yang pernah dinominasikan mendapatkan Nobel dari Indonesia berarti kini berjumlah dua orang, yaitu Pramoedia Ananta Toer dan Denny JA.
Memang penyeleksian penerima hadiah Nobel itu begitu ketat, dan mengapa kedua orang ini yang baru dinominasikan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan objektif yang bisa dipertanggungjawabkan.
Jika menyangkut Denny JA sebagai penggagas puisi esai yang dicalonkan sebagai nominasi penerima hadiah Nobel, kiranya kita bisa berasumsi bahwa genre puisi esai itu menawarkan sebuah bentuk yang relatif baru, dan pengaruhnya tidak hanya di Negara Indonesia, namun menyebar ke negara-negara lainnya.
Dalam persoalan isi, puisi esai pun umumnya tidak berbicara tentang persoalan-persoalan pribadi, seperti patah hati, rembulan yang indah, atau pergulatan diri yang sedang mencari jati diri, namun menyangkut masalah kehidupan sosial seperti toleransi, ketidakadilan sosial, kemiskinan, perjuangan minoritas untuk bisa survive di dalam dominasi mayoritas, dan sebagainya.
Tentu saja dinominasikannya Denny JA sebagai penerima hadiah Nobel tidak lantas secara otomatis nantinya menjadi penerima hadiah Nobel.
Meskipun begitu, dengan masuknya nama itu dalam jajaran nominator memberikan rasa bahagia dan gembira, karena hal itu bukan suatu hal yang mudah.
Denny JA memang kini tak hanya sebuah nama, namun juga menjadi sebuah identitas.
*Penulis adalah Pengamat Sastra dan Teater